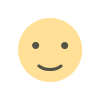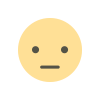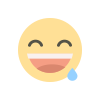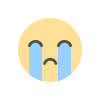Drama Nasional di Panggung Bencana Aceh

Newscyber.id l Lebih dari dua minggu setelah banjir bandang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera, penanganan pemerintah justru menampilkan ironi khas republik ini—negara yang tampak lebih cepat meredam kritik ketimbang mengurus korban. Di tengah lumpur, pengungsian, dan ratusan jenazah yang dievakuasi, publik justru disuguhi rangkaian drama politik yang mengaburkan persoalan utama: lambatnya respons dan absennya kepemimpinan bencana.
Kontroversi yang Mengawali Drama
Ketegangan bermula ketika Kepala BNPB menyatakan bahwa banjir Aceh “tak parah” seperti ramai di media sosial. Pernyataan itu langsung memicu kemarahan publik. Fakta di lapangan bertolak belakang: ribuan warga terjebak, jembatan rubuh, ratusan kilometer jalan terputus, dan listrik padam selama berhari-hari. Setelah kritik memuncak, Kepala BNPB akhirnya meminta maaf pola klasik ketika negara tidak siap namun tetap ingin terlihat menguasai keadaan.
Desakan agar Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional semakin kuat. Beberapa negara bahkan menyatakan kesiapan membantu, termasuk komunitas diaspora Aceh di Malaysia. Namun bantuan itu tersendat karena status bencana yang tak kunjung diberikan. Pemerintah pusat tetap bersikukuh Aceh masih mampu menangani sendiri, sebuah klaim yang kontras dengan situasi lapangan.
Beberapa kabupaten kemudian mengirimkan surat pernyataan ketidaksanggupan. Belakangan diketahui bahwa surat tersebut merupakan arahan Pemerintah Provinsi. Alih-alih menggunakan surat itu untuk mengusulkan status bencana nasional, Gubernur Aceh Muzakir Manaf justru menyebut para bupati sebagai “cengeng”.
Bupati Umrah dan Kekacauan Politik Nasional
Drama berikutnya terjadi ketika Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, salah satu penandatangan surat ketidaksanggupan, viral karena berangkat umrah tanpa izin gubernur. Pemerintah Aceh baru menyampaikan penolakan izin ketika Mirwan sudah berada di perjalanan. Insiden itu melebar menjadi isu politik nasional: Ketua Komisi II DPR mengecam, Mendagri turun tangan, Gerindra memecat Mirwan dari jabatan partai, hingga Presiden Prabowo ikut menyindir keras. Mirwan akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bupati.
Tak berhenti di situ, muncul pula episode “93 persen listrik menyala”. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim pemulihan listrik Aceh telah mencapai 93 persen saat mendampingi Presiden. Warga Aceh yang masih berada dalam kegelapan langsung membantah klaim tersebut. Beberapa hari kemudian, Bahlil meminta maaf, sementara Dirut PLN mengungkap bahwa sistem kelistrikan Aceh mengalami gagal sinkronisasi dan baru diproyeksikan pulih pada 14 Desember.
Esensi yang Tenggelam dalam Kegaduhan
Serangkaian drama itu menyita energi publik dan media, namun justru menenggelamkan isu pokok: mengapa respons negara begitu lambat? Apa penyebab utama banjir sebesar ini? Mengapa pemerintah pusat menolak menetapkan Aceh sebagai bencana nasional? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata bertumpu pada aspek politik dan lingkungan yang jauh lebih kompleks dari sekadar “harga diri negara”.
Penolakan Status Bencana Nasional dan Luka Ekologis Aceh
Secara objektif, hampir seluruh indikator bencana nasional telah terpenuhi. Walhi Aceh mencatat setidaknya lima variabel utama: korban besar, pengungsian masif, kerusakan infrastruktur, wilayah terdampak luas, dan pemerintah daerah kewalahan. Data BNPB pun mengonfirmasi situasi tersebut: per 8 Desember 2025 tercatat 974 korban meninggal, 298 hilang, puluhan ribu mengungsi, dan angka-angka itu terus meningkat.
Pada akhir November, 526 ribu jiwa terdampak. Hanya beberapa hari kemudian, jumlah itu melonjak menjadi lebih dari 1,4 juta jiwa, dengan lebih dari 650 ribu warga mengungsi di 828 titik.
Namun pemerintah pusat tetap menahan status bencana nasional.
Geopolitik dan Kekhawatiran Pemerintah Pusat
Secara geopolitik, Aceh memiliki dinamika pascakonflik yang sensitif. Gerakan ASNLF di luar negeri kembali aktif di forum internasional dan turut menyinggung bencana Aceh dalam pernyataan di UNPO. Penetapan bencana nasional berpotensi membuka akses bantuan asing dalam skala besar, sebuah langkah yang dinilai dapat memicu sensitivitas politik di wilayah bekas konflik ini.
Ekologi Rusak dan Jejak Korporasi Besar
Namun faktor paling signifikan justru terletak pada kerusakan ekologis. Penetapan bencana nasional dapat membuka ruang investigasi yang menyeret banyak korporasi besar: perusahaan tambang, pemegang HGU sawit, hingga pemilik konsesi hutan yang diduga merusak tutupan hutan dan wilayah DAS kritis.
Walhi mencatat 954 DAS di Aceh, dengan 20 di antaranya dalam kondisi kritis. DAS Krueng Trumon kehilangan 43 persen tutupan hutan sejak 2016. DAS Singkil kehilangan 820 ribu hektar hutan dalam sepuluh tahun—setara dua kali luas Jakarta.
Industri ekstraktif berdiri di hulu dalam skema konsesi yang tumpang tindih:
64 perusahaan pemegang IUP
487 ribu hektar HGU sawit
97 ribu hektar konsesi PT Tusam Hutani Lestari
Tumpang tindih konsesi dengan PT Linge Mineral Resources dari BRMS
Perusahaan tambang di Aceh Barat–Nagan Raya yang terhubung dengan jejaring Media Group
Jika investigasi resmi dilakukan, seluruh rantai konsesi, izin, hingga kepentingan bisnis yang berkelindan dengan elite politik nasional dapat tersorot. Di sinilah masalahnya menjadi politis, bukan sekadar administratif.
Banjir Aceh: Bencana Ekologis yang Dibangun Bertahun-Tahun
Banjir Aceh bukan semata hasil curah hujan ekstrem. Ia adalah akumulasi dari gunung yang gundul, sungai dangkal, kanal tambang terbuka, dan deforestasi besar-besaran yang dibiarkan bertahun-tahun. Ketika daya dukung lingkungan runtuh, hujan bukan lagi berkah, melainkan bencana.
Namun narasi resmi lebih memilih menyalahkan “cuaca ekstrem” daripada mengakui jejak panjang perusakan ekologis.
Kini, pertanyaan terbesar adalah:
Apakah Satgas Penataan Kawasan Hutan berani menyentuh perusahaan-perusahaan besar yang diduga merusak DAS?
Atau investigasi ini akan kembali menjadi laporan normatif tanpa menyentuh aktor-aktor inti.
Aceh sedang mengajarkan satu hal penting kepada republik: bencana ekologis tidak terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pembiaran kebijakan, perebutan rente, tumpang tindih izin, dan lemahnya pengawasan. Namun lebih mengerikan dari bencana itu sendiri adalah ketika negara terlihat lebih sibuk memainkan dramanya daripada menyentuh akar persoalan yang merobek Aceh sedikit demi sedikit.
Oleh: Mahmud Padang (Pemerhati Sosial Politik Aceh, Ketua DPW Alamp Aksi Aceh)
(Ramli Manik)